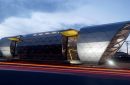Jakarta (Greeners) – Berkebun atau saat ini biasa disebut home farming, merupakan salah satu budaya agraris masyarakat Indonesia. Namun, maraknya bangunan beton di wilayah perkotaan membuat lahan untuk berkebun semakin sempit dan masyarakat perkotaan larut dalam kehidupan yang berorientasi industri. Semakin banyaknya makanan atau bahan pangan impor di Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mandiri dalam sektor pangan.
Menurut pegiat Bekasi Berkebun, Annisa Paramita, kegiatan berkebun sangat bermanfaat bagi masyarakat perkotaan. Menurutnya, dengan berkebun, masyarakat dapat mengetahui dan menjamin kesegaran makanan yang mereka konsumsi.
“Manfaat paling minimal, kita dapat bahan makanan yang kita tahu asalnya dari mana dan juga cara perawatan serta perlakuan tanaman,” jelas perempuan yang biasa disapa Nissa ini kepada Greeners saat dijumpai di kantornya yang berada di daerah Bekasi timur, akhir Desember lalu.
Menurut Nissa, bahan baku makanan yang diproduksi massal sering kali bersentuhan dengan zat kimia tertentu yang mungkin tidak baik bagi tubuh. “Sementara kalau kita melakukan home farming, misalnya kita mau mengulek sambel, ternyata kita menanam cabai beberapa pot, ya sudah, petik saja cabainya dan ulek,” imbuhnya.
Nissa sendiri melakukan home farming sejak 2013 lalu. Baginya, berkebun bukan sesuatu yang rumit. Pesatnya perkembangan teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk mencari metode yang tepat untuk memulai home farming, dari metode konvensional yang menggunakan tanah hingga hidroponik.

Beberapa jenis syuran yang dapat dihasilkan dari “home farming”. Foto: pixabay.com
Tidak hanya menyediakan bahan pangan, kegiatan berkebun juga dapat menjadi alternatif untuk menjauhkan penat dan kejenuhan yang dirasakan masyarakat perkotaan sebagai dampak dari rutinitas pekerjaan sehari-hari. Berkebun juga dapat mendekatkan masyarakat dengan alam meski tinggal di perkotaan.
“Ketika mengajak keluarga atau anak-anak (untuk berkebun), kita akan menanamkan ke mereka bagaimana mengapresiasi alam,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, berpendapat bahwa jauhnya masyarakat perkotaan terhadap pertanian telah dimulai sejak peradaban kuno. Ia menyebut bahwa wilayah perkotaan identik dengan pusat pemerintahan, pemasaran dan jasa sejak tumbuhnya kota-kota kuno pada peradaban Babilonia. Hal itu menurutnya menjadi kecenderungan wilayah perkotaan pada era-era selanjutnya. Akibatnya, pertanian dan alam pun semakin melekat dengan wilayah pedesaan.
“Kemakmuran akibat perekonomian membuat berbagai macam bahan makanan mudah didapat sehingga muncul mantra ‘kenapa harus bersusah payah menanam sendiri?’” jelas Tejo melalui surat elektroniknya kepada Greeners.
Kondisi demikian, lanjutnya, membuat masyarakat wilayah perkotaan semakin tidak menghargai alam. Hal ini diperburuk dengan meningkatnya konsumerisme yang diiringi oleh memudarnya nilai-nilai kolektif atau gotong-royong. Masyarakat perkotaan lebih mengedepankan kekuatan membeli produk, termasuk dalam masalah “perut” dan “meja makan”.
Menurut Tejo, permasalahan di atas adalah hal mendasar yang mengakibatkan masyarakat mudah ‘diracuni’ brand image tertentu, termasuk pendapat bahwa produk impor lebih sehat dan berkualitas.
“Dampaknya bisa kita lihat sekarang ini, Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi produk impor seperti buah-buahan, sayuran, tepung-tepungan dan sebagainya. Padahal produsen pangan kita mampu menghasilkan,” ungkapnya.
Sama halnya dengan Nissa, Tejo pun sangat menyarankan masyarakat melakukan berkebun. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang dinamis akan mengarahkan masyarakat itu sendiri untuk kembali menyelaraskan diri dengan alam. Terlebih, menanam dan berkebun merupakan bagian dari budaya dalam kehidupan agraris Indonesia.
“Kegiatan home farming ini bisa dikemas secara menyenangkan dan massal. Demikian juga pengenalan atau edukasi pangan lokal dan sehat. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait,” tutup Tejo.
Penulis: TW/G37