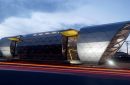Jakarta (Greeners) – Respon pemerintah mengatasi ancaman krisis pangan dengan membangun food estate dinilai keputusan tergesa-gesa dan agresif. Kehadiran proyek food estate hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
Food estate bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelum tahun 2019, ada beberapa kali percobaan pembangunan proyek yang tersebar di berbagai daerah luar Pulau Jawa. Dua yang paling mencolok, yakni PLG di masa Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah dan MIFEE di Papua.
Mengacu dari pengalaman tersebut, proyek-proyek food estate dinilai gagal untuk menjawab permasalahan ketahanan pangan.
Senior campaigner Kaoem Telapak Andre Barahamin menilai, pemerintah tak belajar dari pengalaman kegagalan proyek food estate.
“Atas nama ancaman ketahanan pangan yang FAO keluarkan jadi alasan seolah ini merupakan satu-satunya solusi yang tepat merespon ancaman pangan. Narasi ini terus diulang, padahal gagal dan tak ada dampak positifnya,” katanya dalam media briefing Kaoem Telapak di Jakarta, Rabu (30/11).
Untuk mendukung suksesnya pembangunan food estate, pemerintah memasukkannya ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Imbasnya, ada percepatan perizinan dan kemudahan regulasi untuk menyelesaikan pembangunannya.
Selain itu, UU Cipta Kerja memberi peluang konversi lahan secara masif untuk mempercepat PSN. Ironisnya, hak ekslusif pengelolaan hutan masyarakat dan komunitas adat dicabut pascaregulasi ini terbit.
Food Estate Beri Dampak Negatif
Andre menyebut, pembangunan food estate memberi berbagai dampak negatif. Seperti ancaman pembukaan lahan skala masif di kawasan hutan di wilayah Humbang Hasundutan, Sumatera Utara hingga 2.711 hektare (ha). Adapun di dalamnya termasuk hutan kemenyan yang komunitas masyarakat adat miliki.
Untuk mendukung suksesnya pembangunan food estate di kawasan yang berstatus areal penggunaan lain (APL), pemerintah juga menggandeng perusahaan-perusahaan swasta dengan total proyek seluas 785 ha.
Sementara di Pakpak Bharat, luasannya akan mencapai 8.000 ha. Andre menyebut ancaman deforestasi tak sekadar alih fungsi lahan. Sebab ada praktik politis pembukaan lahan, pengambilan kayu untuk mendukung investasi lain.
Selain itu, food estate bentuk pemborosan anggaran. Berdasarkan pemeriksaan struktur anggaran Kabupaten Ketapang pada periode 2020-2022, Kaoem Telapak menemukan penggunaan anggaran publik agar wilayah ini menjadi lokasi food estate.
“Misalnya rehabilitasi irigasi permukaan di Teluk Keluarga memakan biaya hingga Rp 2,5 miliar rentang tahun anggaran 2020-2021. Lalu pembangunan infrastruktur jalan yang akan menghubungkan bakal lokasi proyek dengan ibu kota kabupaten hingga Rp 7,8 miliar dari APBD Ketapang,” paparnya.
Selain itu di Pakpak Bharat, untuk tahun anggaran 2022, Dinas Pertanian Daerah berencana membeli alat berat pendukung kegiatan food estate sebesar Rp 10 miliar.
Rentan Picu Konflik Sosial
Pembangunan food estate juga rentan memicu memicu konflik sosial. “Ketika ada pembukaan lahan secara masif maka mendorong konflik sosial berkepanjangan, baik antar kelompok maupun dengan pemerintah,” ungkapnya.
Sejatinya, pembangunan proyek food estate mengacu pada PSN berfokus pada wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Namun, berdasarkan temuan Kaoem Telapak, terdapat beberapa daerah yang gencar ingin membangun proyek food estate. Padahal wilayah ini tak masuk dalam PSN.
“Seperti halnya Ketapang, Kalimantan Barat. Padahal proyek food estate di sini pernah gagal. Menteri BUMN, Dahlan Iskan tahun 2012-2012 menargetkan luas lahan hingga 100.000 ha dan terealisasi hanya 0,1 persen,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat Sumatera Utara Delima Silalahi juga berpendapat senada.
Menurutnya, pembangunan food estate hanya berpihak pada koorporasi dan merampas tanah rakyat. Di wilayah Batak yang mempunyai wilayah adat bahkan terimbas. Pemerintah menerapkan sistem sewa ke masyarakat di tanah APL.
Artinya, ini merupakan bentuk perampasan tanah-tanah adat untuk lokasi food estate. “Selain itu pemerintah juga mendorong OPD pemerintah untuk menyewa tanah masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga menyorot perubahan petani yang awalnya polikultur menjadi petani monokultur. Komoditasnya pun hanya bawang merah, bawang putih, hingga kentang.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin