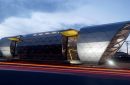Jakarta (Greeners) – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) menjadi undang-undang pada Selasa, (9/7). Greenpeace Indonesia menilai UU tersebut sebagai komitmen semu untuk konservasi alam dan perlindungan masyarakat adat.
Menurut Greenpeace, ada sederet masalah dalam proses formil maupun substansi UU KSDHE. Secara formil, proses pembahasan rancangan UU KSDAHE sangat minim pelibatan masyarakat.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji mengatakan bahwa pembahasan rancangan UU KSDAHE tidak berjalan secara transparan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga kesulitan untuk memonitor prosesnya.
“Pemerintah dan DPR patut ditengarai telah mengabaikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU KSDAHE,” kata Sekar lewat keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).
Secara substansi, lanjutnya, UU KSDAHE juga bermasalah. Undang-Undang Konservasi ini masih menggunakan paradigma lama yang mengeksklusi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perlindungan ekosistem.
UU KSDHAE Tak Mengakomodasi Usulan Masyarakat Sipil
Ia menilai bahwa pemerintah dan DPR tak mengakomodasi usulan masyarakat sipil agar memastikan adanya pengakuan, partisipasi, dan perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam UU KSDAHE.
Kendati ada pasal yang menyebut peran serta masyarakat, termasuk masyarakat adat, proses itu tampaknya hanya dipandang sebagai formalitas belaka. Proses penetapan kawasan konservasi dalam UU KSDAHE bersifat sangat sentralistik karena berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Tersisa 17,7 Juta Ha, Wilayah Masyarakat Adat Butuh Pengakuan
“Hal ini amat berpotensi memicu konflik dengan masyarakat setempat yang kehilangan ruang hidup dan tempat beraktivitas. Watak yang sentralistik ini diperparah dengan pasal-pasal sanksi pidana dalam UU KSDAHE terhadap perorangan yang berpotensi menambah deret panjang kriminalisasi warga,” tambah Sekar.
Menurut Sekar, prinsip konservasi seharusnya mengacu pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention of Biological Diversity)–yang telah pemerintah Indonesia ratifikasi dalam UU Nomor 5 Tahun 1994.
Konvensi tersebut mengatur bahwa negara mestinya mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah masyarakat asli dan masyarakat setempat. Hal tersebut juga berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Greenpeace Indonesia menilai UU KSDHE sebagai komitmen semu untuk konservasi alam dan perlindungan masyarakat adat. Foto: DPR RI – Runi/Andri
Greenpeace Soroti Pembangunan Panas Bumi
Sementara itu, Greenpeace juga menyoroti permasalahan lainnya dalam UU KSDAHE. Salah satunya yaitu pemanfaatan jasa lingkungan untuk beberapa hal, seperti panas bumi dan karbon. Menurut mereka, hal ini secara jelas kontradiktif dengan tujuan konservasi sumber daya alam demi menyelamatkan keanekaragaman hayati yang tersisa.
Kemudian, sistem operasional ekstraksi panas bumi juga sangat berisiko. Hal itu berpotensi mencemari, merusak lingkungan, dan mengganggu ekosistem dalam area hutan.
“Pembangkit terbarukan skala besar, termasuk hydro dan geothermal, membutuhkan pengawasan yang jauh lebih ketat mengenai analisis risiko dan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungannya,” ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto.
Menurut Hadi, pembangunan pembangkit panas bumi yang berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan masyarakat adat serta area yang berpotensi besar menimbulkan konflik sosial berdampak jauh lebih besar daripada manfaatnya. Padahal, transisi ke energi terbarukan harus memastikan aspek keadilan dan keberlanjutan.
Adapun pemanfaatan jasa lingkungan berupa karbon, hal ini secara jelas telah mengindikasikan niat pemerintah berbisnis karbon.
“Ini memungkinkan perusahaan pencemar lingkungan melakukan praktik greenwashing dengan menggunakan uangnya untuk bisnis konservasi,” tambah Hadi.
UU KSDHE Belum Perhatikan Pelestarian Laut
Greenpeace menilai, UU KSDAHE tak akan cukup untuk mencapai target 30×30 guna melindungi setidaknya 30 persen daratan dan 30 persen lautan pada 2030, yang telah disepakati dalam Kerangka Kerja Biodiversitas Kunming-Montreal 2022. Apalagi, substansi UU KSDAHE juga masih cenderung bias darat, misalnya dalam pengaturan area preservasi yang tidak memasukkan pelestarian di area laut.
BACA JUGA: Hari Masyarakat Adat Sedunia: Pandemi Tegaskan Resiliensi Masyarakat Adat
Padahal, hingga 2020, lebih dari 54 persen kawasan hutan sudah menjadi kawasan lindung. Namun, saat ini hanya 8,7 persen kawasan penting laut yang telah dilindungi secara hukum. Pemerintah berencana menambah luasan kawasan lindung laut hingga 32,5 juta hektare pada 2030. Kemudian, secara bertahap menjadi 30 persen di tahun 2045.
“Kita menghadapi ancaman krisis iklim dan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Namun, pemerintah dan DPR masih saja bermain-main dengan komitmen pelindungan lingkungan yang sifatnya semu,” kata Sekar.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia